
Tidak ada yang kunanti melebihi akhir pekan, atau hari pertama sekolah setelah libur yang panjang. Tidak ada. Kecuali sebuah ajakan yang Ayah sampaikan padaku di dapur rumah tepat seminggu yang lalu : Ayah akan mengajakku dan Seruni ke pasar kalangan!
Ayah sukses menyogokku untuk menjadi anak baik lewat ajakan tersebut. Seharian itu, aku berganti identitas dari anak nakal berbau matahari menjadi anak buyung berambut klimis disisir menyamping. Sepulang sekolah, aku berganti pakaian dengan rapi, makan siang tepat waktu, mengerjakan semua PR dan membantu Ibu dan Kakek mengurus ternak dan kebun sepanjang sore. Begitu terus setiap hari selama seminggu.
Hanya Seruni yang paham perasaanku pada saat itu. Betapa lama kami menanti kesempatan itu. Benar-benar istimewa!
- - - - - - - - - - -
Dari ukurannya, rumah panggung kami jelas tidak seberapa megah. Kecil, sebenarnya, namun nyaman. Sejuk di musim kemarau dan hangat di musim hujan. Jika kau menuruni bukit dari arah balai desa pada awal tahun, kau bisa melihat dengan jelas asap tungku mengepul keluar dari dapur di belakang rumah kami. Mungkin saat itu Ibu sedang merejang tempoyak udang sungai kesukaanku dan Seruni, hidangan keluarga penyambut musim tanam.
Majulah 30 langkah, lalu kau bisa melihat rumah kami seutuhnya. Di sampingnya berdiri terpisah sebuah gubuk yang berfungsi sebagai penampungan kayu bakar, menempel dengan kandang kambing. Di belakangnya, terhampar sepetak kebun yang ditumbuhi aneka sayuran, juga sebatang pohon duku dan sebatang pohon manggis. Anggrek liar beraneka warna dan melati tumbuh merambati pagar kebun, berebut tempat dengan lumut tanduk dan jamur payung yang tumbuh subur karena udara hutan yang lembab. Di balik pagar tersebut, Bakung dan Seroja dilepas ketika malam menjelang, menjadi penghalau babi hutan dan musang yang hendak bertandang ke kebun tanpa membawa undangan. Mereka adalah dua ekor anjing betina yang kami pelihara sejak kecil.
Tetangga? Dalam radius 100 meter, kami bertetangga dengan rerumpunan pohon cemara dan keluarganya, pohon jati dan teman-teman gengnya, juga pohon damar, pohon kenari dan pohon trembesi, lengkap dengan kera-kera, hewan-hewan pengerat dan burung-burung yang bersarang di tiap dahan dan lubang yang ada pada mereka.
Konon dahulu kala, kakek buyut kami kabur ke tengah hutan ini ketika perang berkecamuk di kota, saat harga sekarung beras setara dengan nyawa manusia. Kakek buyut lalu membangun pondok kayu untuk berteduh, bertahan hidup dengan memakan buah-buahan dan umbi-umbian hutan, lalu terus menetap disana hingga Malaikat Izrail mengetuk pintu gubuknya. Gubuk tersebutlah, yang kemudian kami bangun ulang dan kami ubah namanya menjadi ‘rumah’. Disanalah keluarga kecil kami terus berinduk-semang hingga saat ini.
Aku tinggal berlima, bersama Kakek, Ibu, Ayah, dan adik perempuanku Seruni. Meski keluarga kami kecil, kami punya job description masing-masing yang sama sekali tidak remeh. Ibu, misalnya, sehari-hari bertugas mengurus rumah, kebun sayur, dapur, juga aku dan Seruni. Ibu juga bertanggung jawab mendayagunakan waktu luangnya untuk membuat kerajinan dari daun nipah kering. Ayah bertugas pergi ke hutan, mengumpulkan getah karet, kayu bakar dan sesekali ikan dan udang sungai. Lain dengan Kakek, yang tugasnya duduk di kursi di teras depan rumah dan menatap kejauhan, sambil sesekali menggerutu tentang kakinya yang kram atau pinggangnya yang nyeri. Jika sedang tidak bertugas, Kakek biasa menggunakan waktu luangnya untuk membenarkan radio yang rusak atau merusakkan radio yang benar dengan obeng.
Job description-ku dan Seruni adalah yang paling spesial. Tiap Senin sampai Sabtu pukul delapan pagi hingga satu siang, kami wajib berada di sekolah dan belajar. Di antara kami berlima di keluarga ini hanya aku dan Seruni yang pernah mendapat tanggung jawab sebesar dan seistimewa itu. Misi perdana dalam garis keluarga kami. “Biar nasib kalian lebih baik dari Ayah dan Ibu”, begitu kata Ayah tiap kali kami sungkan beranjak dari kasur di pagi hari. Meski terkadang malas sekali melakukannya, tapi kami pada akhirnya selalu berangkat ke sekolah dan menjalankan dinas kami dengan sukses. Semuanya berkat siraman rohani dari Ayah dan siraman air dingin dari Ibu.
Biasanya sekali atau dua kali dalam sebulan, Ayah berangkat ke pasar kalangan di ibukota kecamatan untuk menjual hasil kebun dan kerajinan nipah, lalu membelanjakan hasil penjualannya dengan kebutuhan lain. Dan tidak seperti saat-saat sebelumnya, kali ini aku dan adikku akan ikut!
“Habis Subuh besok. Jangan kesiangan”, pesan Ayah. Dan hanya kata-kata itulah yang kami tunggu selama ini. Maka jelaslah sudah, malamnya aku dan Seruni tidak bisa tidur nyenyak.
- - - - - - - - - - -
Di usiaku yang sembilan tahun, aku belum mampu membayangkan tempat yang lebih ramai dan padat dari Pasar Kalangan. Belum pernah mengunjungi lebih tepatnya. Berbagai kendaraan berlalu-lalang di atas jalan yang beraspal dan tidak beraspal. Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Beroda empat, tiga, dua, satu atau ditarik hewan ternak. Membuang asap knalpot atau mencurahkan kotoran.
Beberapa orang bahkan memasuki pasar dari atas : naik helikopter, ambal ajaib atau naga yang dijinakkan. Melempar tali-temali, tangga-tetangga, lalu menggelar lapak diatas udara. Yang dibawah tidak kalah seru. Beberapa barang dagangan tampak tak biasa. Penjual daging menyajikan daging badak, harimau sumatera, ikan arwana, gading gajah dan hewan-hewan pengerat kecil asing yang diawetkan dalam stoples di atas etalase sederhana. Selain daging, ada juga pedagang pakaian bekas, biasa disebut Buruan Jambi, juga pedagang kue, manisan, buah-buahan segar, ikan hias, sirip ikan hiu, racun komodo, racun ular kobra, VCD bajakan dan masih banyak lagi. Jariku tak cukup demi menghitunginya.
“Disini bagus juga untuk menggelar lapak”, kata Ayah, menunjuk sepetak ruang sempit diantara penjual obat kuat dan daging Harimau Sumatera. Aku hendak mengeluh, tapi tak keluar sepatah kata pun dari mulutku. Beberapa detik kemudian, lapak sudah terbentang dengan ajaibnya.
Kami duduk di belakang tumpukan sayuran, duku dan bakul nipah jualan kami. Aku sendiri duduk di belakang ayah, menatapi kepala Harimau Sumatera yang tergantung di sebelahku. Tampak sangar, tapi juga merana jika dilihat lebih seksama. Rahangnya menganga. Lalu tampak sebutir air mengalir jatuh dari atas pipinya yang loreng.
“Tolong aku”, katanya.
Lalu aku terbangun, terpekik dalam diam.
Waktu masih dini hari, namun hujan lebat turun di luar.
(Bersambung...)

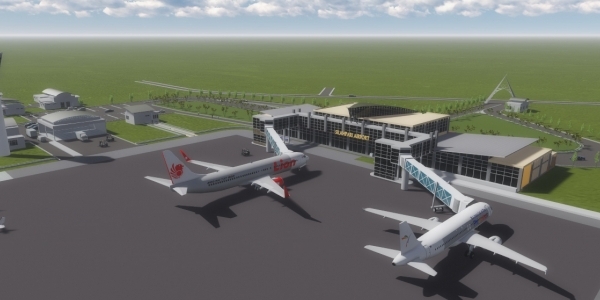

Bagaimana menurutmu kawan?
Berikan komentarmu